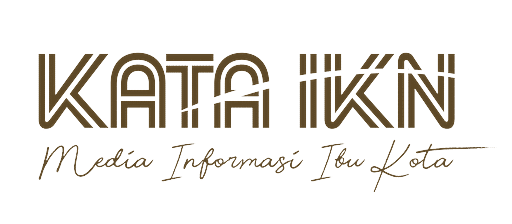Oleh : Edwin Irawan*
Agustus kembali datang. Bulan ketika udara pagi terasa lebih khidmat, jalan-jalan mulai dipenuhi merah putih, dan langit-langit kampung berubah jadi hamparan lambang kebanggaan bangsa. Namun tahun ini, di antara semangat kemerdekaan yang tengah dipupuk, muncul satu fenomena tak biasa: bendera bajak laut dari manga One Piece, lengkap dengan simbol tengkorak dan topi jerami, ikut berkibar di mobil, rumah, bahkan tiang-tiang jalanan.
Di media sosial, pemandangan ini ramai dibicarakan. Banyak dari pemasangnya adalah penggemar setia Luffy dan kru Topi Jerami. Sebuah bentuk ekspresi kecintaan terhadap karakter fiksi yang dikenal gigih, berani melawan ketidakadilan, dan tak tunduk pada kekuasaan yang menindas.
Namun di balik gelombang viral itu, muncul tanya yang tak bisa diabaikan: bolehkah sebuah simbol perlawanan, meski hanya fiksi, disandingkan dengan sang saka merah putih — lambang paling suci milik bangsa ini?
Dalam konteks dunia One Piece, bendera bajak laut adalah lambang perlawanan terhadap Pemerintah Dunia yang korup. Ia simbol pemberontakan, ketidakpatuhan, dan semangat membebaskan diri dari tirani. Tapi Indonesia bukan dunia fiksi. Merah putih kita bukan kain biasa, melainkan penanda identitas, simbol persatuan, dan warisan sejarah berdarah.
Bendera merah putih lahir dari perjuangan. Ia bukan sekadar kain dua warna. Di baliknya ada kisah para pejuang yang meregang nyawa di medan perang, ada tangis ibu-ibu yang melepas anaknya ke garis depan, dan ada sejarah panjang bangsa yang pernah dijajah berabad-abad lamanya.
Ketika bendera itu berkibar setiap 17 Agustus, bukan hanya kenangan yang dibangkitkan — tapi juga tekad, rasa hormat, dan tanggung jawab untuk menjaganya tetap berkibar, utuh dan tidak ternoda.
Maka ketika bendera lain — apa pun itu, bahkan jika hanya tokoh kartun sekalipun — dikibarkan berdekatan, apalagi disandingkan di satu tiang atau tempat yang sama, pertanyaannya bukan soal suka atau tidak, tapi soal layak atau tidak.
Mereka yang memasang bendera bajak laut itu boleh jadi tak bermaksud merendahkan. Sebagian besar tetap mengibarkan bendera merah putih di atasnya, mungkin sebagai penanda bahwa mereka tahu batas. Tapi batas itu tetap kabur, dan jika terus dibiarkan, bisa menjadi kebiasaan yang memudar makna.
Boleh marah pada negeri ini, boleh kecewa pada penguasa. Tapi jangan pernah menyandingkan kemarahan itu dengan lambang negara. Sebab ketika yang disentuh adalah simbol pemersatu bangsa, maka yang terusik bukan hanya pemerintah, tapi seluruh rakyat Indonesia.
Agustus ini, alangkah baiknya jika rumah-rumah kembali dipenuhi kibaran merah putih yang gagah. Bukan sekadar kewajiban, tapi wujud cinta. Di tengah banyaknya isu luar negeri, perang, dan konflik geopolitik, bangsa ini butuh satu hal paling mendasar: kesatuan.
Kita boleh mencintai karakter fiksi, mengagumi semangat Luffy yang tak kenal takut, tapi jangan sampai lupa — pahlawan kita yang sesungguhnya bukan dari manga, tapi dari sejarah. Dari pejuang-pejuang yang tak punya kekuatan super, tapi punya keberanian untuk memperjuangkan satu hal: kemerdekaan.
Dan itulah mengapa, merah putih tak boleh dibandingkan, apalagi disandingkan. Sebab ia bukan sekadar bendera. Ia adalah kita. Kita yang merdeka.
*Penulis adalah Komisioner Bawaslu Penajam Paser Utara (PPU)